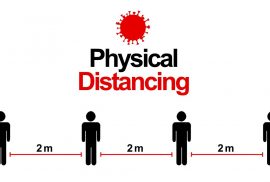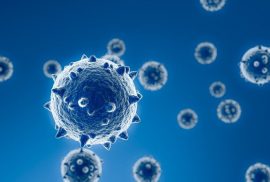Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM mengadakan Web Seminar (Webinar) bertajuk Meneropong Kebijakan Physical Distancing pada Kamis, 14 Mei 2020 pukul 10.00-12.00 WIB.
Pola penularan COVID-19 yang mengikuti laju eksponensial memaksa masyarakat untuk menerapkan physical distancing, bahkan banyak negara kemudian mengeluarkan kebijakan full lockdown atau partial lockdown untuk memperlambat atau menurunkan tren penularan pandemi tersebut. Indonesia mulai memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak 7 April 2020 khususnya untuk daerah episentrum COVID-19 seperti Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
Dr. Hakimul Ikwan selaku dosen FISIPOL UGM dan peneliti PSKK UGM berpendapat bahwa semua negara saat ini terdampak COVID-19, tidak terkecuali negara yang disebut paling modern dan ‘superior’, seperti Amerika. Namun tidak semua negara mengalami keterpurukan, misalnya Taiwan dan Vietnam.
Meski situasi saat ini (physical distancing) memaksa masyarakat berjarak secara fisik, masyarakat seharusnya juga tidak berjarak secara emosional karena senyatanya semua orang sedang menghadapi ‘keadaan’ yang sama. Namun, menurut Hakim, saat ini terdapat indikasi yang cukup kuat terhadap tumbuhnya perpecahan kedekatan emosional di Indonesia.
Hakim menyoroti bahwa keterpurukan di Amerika terjadi salah satunya karena hilangnya kepercayaan masyarakat (distrust) kepada para pemimpin negara, contohnya keterpecahan politik yang luar biasa antara pendukung republik dan demokrat. Sementara itu, hal sebaliknya terjadi di Taiwan dan Vietnam yang melakukan sistem “cerdas berjarak”. Taiwan bahkan tidak ragu memutus hubungan dengan China meski ikatan keduanya sangat kuat. Kedua negara tersebut berhasil belajar dari Hongkong yang tidak melakukan keterbukaan data saat awal virus corona mulai merebak.
Dari tiga pilar kesejahteraan sosial, yaitu tanggung jawab negara, kontribusi wajib, dan sukarela atau voluntarisme, Hakim menilai, pilar yang tersisa saat ini dan memberi sesercah harapan untuk mencegah terjadinya perpecahan emosional masyarakat adalah pilar ketiga, yaitu sukarela atau voluntarisme atau solidaritas sosial.
Hasil survey PSKK UGM (2020) yang dilakukan secara daring menunjukkan, 80 persen masyarakat bersedia memberi donasi dalam bentuk sembako dan 76,2 persen menyatakan akan berdonasi dalam bentuk uang. 34,2 persen bersedia mengantarkan langsung bantuan ke penerima, 24,7 persen melalui lembaga atau pihak ketiga, 22,2 persen melalui donasi secara daring, 18,9 persen tidak berlaku, dan 22,2 persen mengatakan akan berdonasi secara daring.
“Indonesia (saat ini) ada di jurang distrust karena di satu sisi memiliki prakondisi Amerika (keterpecahan), namun di sisi lain tidak memiliki anti body Taiwan dan Vietnam (cerdas berjarak). Pemerintah seharusnya belajar dari Taiwan dan Vietnam dan pemerintah juga harus membangun kepercayaan publik,” tegas Hakim.
Ketua MUI DIY bidang SDM, budaya, dan seni sekaligus dosen UIN Sunan Kalijaga, Dr. Tulus Mustofa menjelaskan bahwa islam juga mengajarkan pentingnya memupuk sikap solidaritas dalam menghadapi pandemi. “Pertama-tama untuk membangun solidaritas itu sangat penting karena apa pun yang kita rancang sebagai umat atau bangsa itu sulit tercapai jika umat atau bangsa tidak solid. Suatu wabah tidak hanya dilihat sebagai musibah tapi juga peluang beramal membantu orang lain, sekaligus bagian menjauhkan musibah tersebut,” ujar Tulus.
Komunikasi Kebijakan di Era COVID-19
Dosen FISIPOL UGM sekaligus Ketua Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT), Prof. Hermin Indah Wahyu memaparkan bahwa karakter kebaruan dari virus corona menjadikan lingkungan informasi uncertain (tidak menentu), oleh sebab itu strategi komunikasi yang diambil harus sangat tepat dan sampai pada orang yang tepat pula.
“Dalam persoalan pandemi, pencegahan meluasnya eskalasi penularan menjadi kata kunci penting, sehingga cara apa yang dipilih akan menjadi sukses atau tidaknya sebuah negara untuk keluar dari perjuangan melawan corona,” ujar Hermin.
Kualitas komunikasi publik (di Indonesia) dalam menghadapi pandemi, menurut Hermin, setidaknya mengalami beberapa masalah, seperti pemaparan strategi oleh pihak-pihak yang relevan tanpa basis data yang kuat (No evidence Based Policy), kegagalan komunikasi interpenetrasi, dan tidak adanya komunikasi dalam skenario besar yang menjadi strategi dasar melawan COVID-19.
Sehubungan dengan pilihan upaya intervensi untuk reduksi penyebaran virus, masyarakat perlu diajak untuk memahami apa yang sedang dihadapi serta bagaimana pilihan-pilihan strategi akan berkontribusi pada pengurangan eskalasi. Peran para ahli epidemi sangat penting untuk memberikan basis data yang menjadi panduan gerak langkah pemerintah.
“Namun, yang terjadi di Indonesia kita terkaget-kaget karena pilihan-pilihan arah kebijakan yang tidak atau kurang jelas dasar pemikirannya. Para ahli epidemi harusnya dapat panggung yang kuat karena mereka ahlinya. Tetapi, di Indonesia ahli epidemi malah tidak ada panggung sama sekali,” ungkapnya.
Sementara dalam kegagalan komunikasi interpenetrasi ditandai oleh dominasi sistem internal tertentu dalam merespons krisis seperti COVID-19. “Contohnya, corona dalam filter sistem perhubungan, corona dalam filter sistem ekonomi, corona dalam filter sistem hukum,” papar dosen Komunikasi UGM tersebut.
Selain itu, menurutnya terjadi too much resonance atau terlalu banyak cabang isu yang digaungkan para pemangku kebijakan dan semua sistem itu mengutarakan pandangannya masing-masing sesuai dengan karakter fungsi sistem internalnya, sehingga semakin jauh dari persoalan utama pandemi corona, yaitu kesehatan.
“Wacana publik mengenai PSBB difilter oleh banyak sistem sehingga sulit menghindarkan konflik wacana yang sangat potensial terjadi,” jelasnya. Selain itu, tidak ada komunikasi dalam skenario besar yang menjadi strategi dasar melawan virus corona, sehingga masyarakat sulit membayangkan sedang dalam fase apakah Indonesia saat ini (normal, kritis, atau landai?).
“Dikemukakan angka-angka update oleh juru bicara kemenkes setiap harinya untuk update data terakhir, namun apa makna informasi tersebut dalam bingkai strategi makro kurang dapat ditangkap. Koordinasi oleh presiden dan staf, dan gugus tugas penanganan COVID-19 oleh BNPB memiliki warna informasi yang kurang lebih sama. Idealnya, presiden memberi pandangan yang lebih makro substantif menggerakkan koordinasi berbagai elemen,” tegas Hermin.
“Potret komunikasi kebijakan yang sangat terfragmentasi sulit untuk dapat membayangkan gambar besar seperti apa yang ada saat ini di benak publik: uncertain (tak pasti), semuanya sama dan sejajar,” pungkasnya.
Materi seminar Meneropong Kebijakan Physical Distancing bisa diunduh di sini: tautan materi
Penulis: Nuraini Ika dan Nurul Widia | Editor Bahasa: Rinta Alvionita | Foto: Ramlon (pixabay.com)