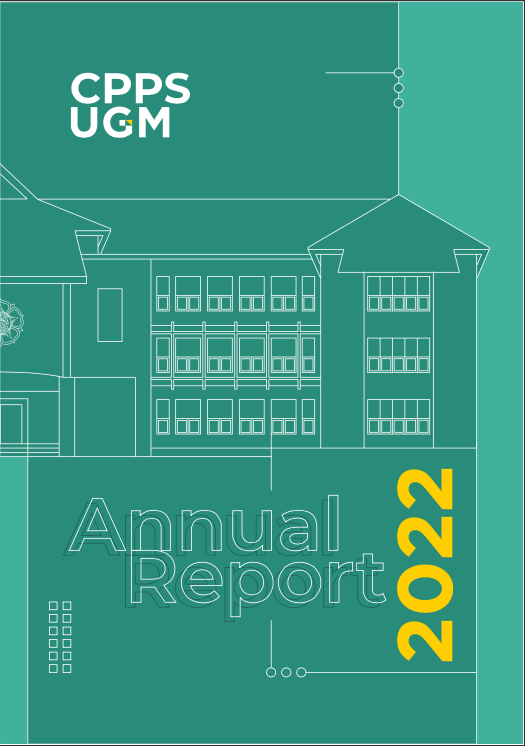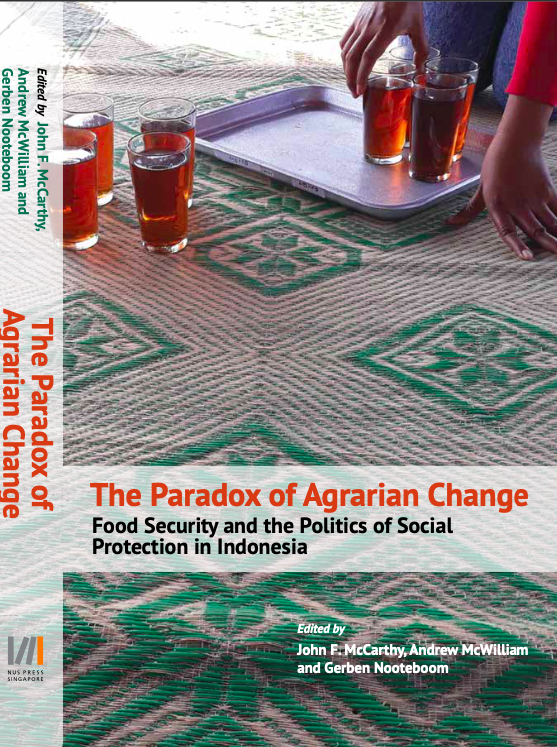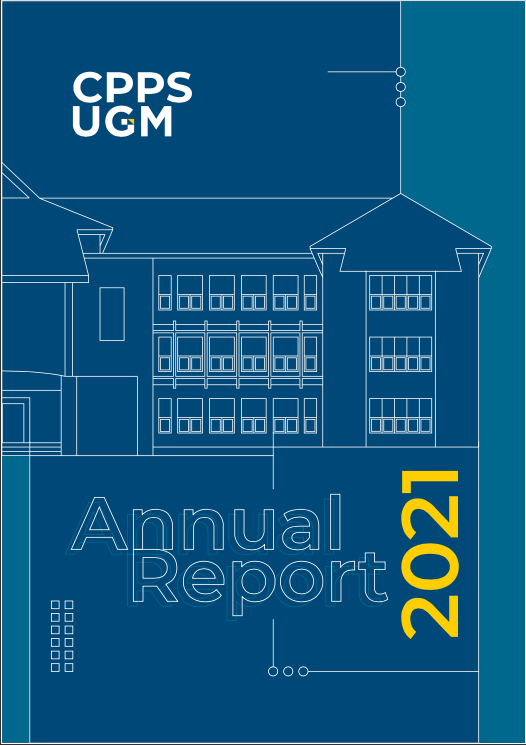MANJI Oleh: Muhadjir Darwin
|Esai & Opini, Media

Massa dari kelompok radikal mengamuk di tempat acara dengan merusak bangunan dan menganiaya peserta diskusi. Lengkaplah sudah. Yogyakarta sudah tercoreng citranya sebagai kota pluraris yang damai. Kebebasan akademis, termasuk kebebasan berbicara, juga sudah mati di Kampus Biru. Dengan ‘takluk’ pada tekanan ormas atas tampilnya Manji, kampus sudah bukan lagi lingkungan yang terbua bagi berkembangnya gagasan-gagasan yang berbeda.
Praktik kekerasan berbasis agama sudah berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Tetapi apa yang ditakutkan dari seorang Irshad Manji? Saya menjadi pembicara banding pada waktu Manji tampil di SPS UGM lima tahun yang lalu. Tidak ada yang aneh dari pikiran-pikirannya. Dia menganjurkan tentang kebebasan berijtihad dalam Islam. Islam toleran terhadap perbedaan, karena itu orang Islam tidak perlu takut menyuarakan pikiran-pikirannya. Islam juga tidak bisa dijadikan instrumen untuk melakukan kekerasan terhadap pihak lain yang punya keyakinan berbeda.
Pendapat seperti itu bukan hal baru di Indonesia. Para reformis Islam sejak Ahmad Dahlan sampai Nurcholis Majid dan Abdurachman Wahid sudah lama menyuarakannya. Pendapat seperti itu justru penting sebagai ant-tesis terhadap praktik kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal di Indonesia, seperti kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah atau penganut agama minoritas. Praktik kekerasan yang kemudian dilakukan terhadap kehadiran Manji justru membenarkan tesis Manji, bahwa Islam telah dibawa ke jalan yang keliru, yaitu jalan kekerasan dan anti kebebasan berpikir.
Keberatan yang diajukan oleh para penentang Manji adalah pada kenyataan bahwa Manji adalah seorang lesbi. Manji memang secara terbuka mengakui tentang orientasi seksualnya itu. Tetapi dia ingin bicara di Indonesia bukan tentang orientasi seksual tersebut. Pada penampilan pertamanya di UGM, satu kata pun tidak keluar dari mulutnya tentang hal itu. Melarang orang berbicara karena orientasi seksual tertentu jelas melanggar hak. Ini merupakan gerak mundur, terutama bagi UGM, karena UGM sudah berada di depan untuk memperjuangkan hak-hak kaum minoritas. Sebagai orang UGM saya kecewa.
Seksualitas juga bukan topik yang tabu bagi UGM untuk didiskusikan secara terbuka. UGM bahkan telah sering menjadi tuan rumah dari seminar internasional tentang hak-hak seksual, dan sudah barang tentu menghadirkan sejumlah pembicara dan dihadiri peserta yang mempunyai orientasi seksual berbeda. Pada Maret 2007 UGM menjadi tuan rumah Konferensi Internasional tentang Hak-hak Seksual. Di konferensi itu keluar Deklarasi Yogyakarta yang salah satu pasalnya menyatakan: “Semua manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam kehormatan dan hak. Semua manusia, apapun orientasi seksual dan identitas gendernya berhak menikmati hak-hak dasarnya sebagai manusia”. Selain itu, pada 2010 Kartini-Asia berhasil menggelar international workshop on Sexual Rights di UGM. Setahun berikutnya, 2011, UGM menjadi tuan rumah Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health and Rights. Di kedua acara tersebut, isu-isu hak-hak seksual kaum minoritas dibicarakan secara terbuka.
Ketika itu, dunia melihat Yogya bukan hanya sebagai a city of culture (kota budaya), a city of education (kota pendidikan) seperti yang selama ini dikenal. Tetapi juga a city of pluralism (kota pluralsime) dan a city of tolerance (kota yang penuh toleransi). Adakah citra itu sudah tinggal cerita masa lalu?
(Dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat, Minggu 13 Mei 2012)
*sumber foto: Solo Pos