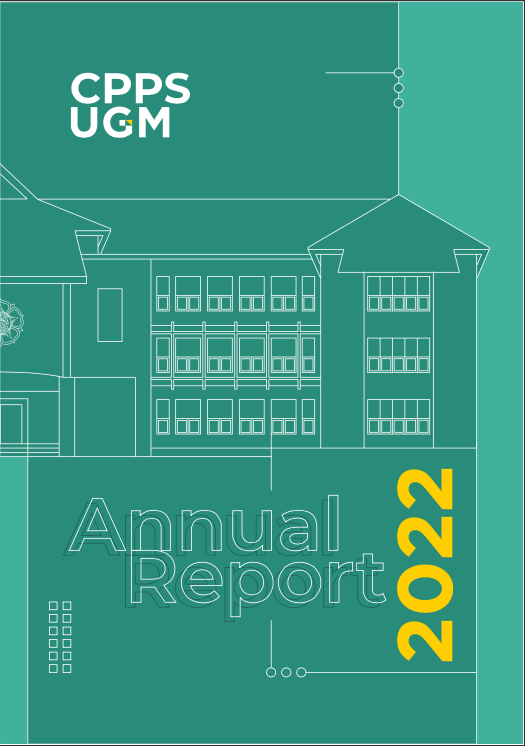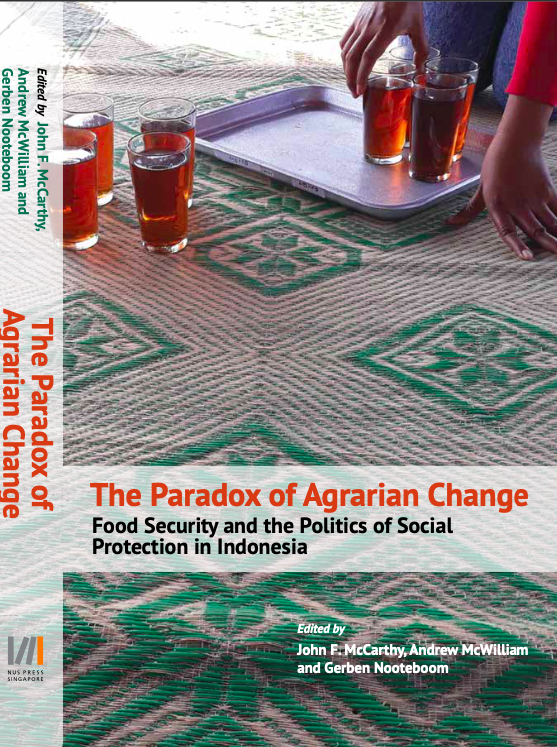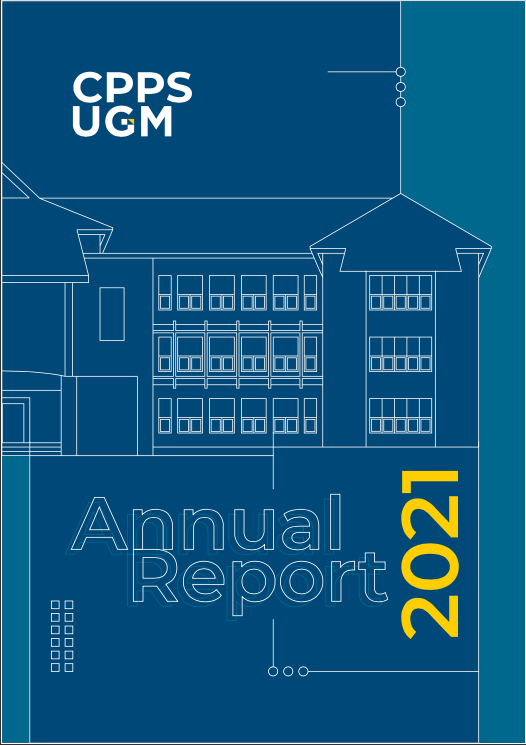KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK
|Masalah kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja disebabkan makin beragamnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. Kekerasan terhadap perempuan terjadi di berbagai belahan bumi dan pada umumnya si pelaku adalah laki-laki. Di Amerika Serikat misalnya, laporan C.Everett Kopp pada tahun 1989 menunjukkan bahwa sembilan dari sepuluh pembunuhan terhadap perempuan dilakukan oleh laki-laki. Di Bosnia, sedikitnya 20.000 perempuan Bosnia diperkosa oleh tentara Serbia, dan di India, terjadi 11.252 pembunuhan yang berkaitan dengan mas kawin dalam tiga tahun terakhir (Jurnal Perempuan, 1999: 25).
Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap perempuan pun tampak semakin meningkat baik ragam maupun intensitasnya. Data dari Mitra Perempuan menunjukkan bahwa setiap 5 jam, ditemui 1 kasus perkosaan (Arivia, 1998: 7). Sejauh itu, perhatian terhadap kasus tindak perkosaan belum begitu maksimal. Penanganan terhadap kasus perkosaan masih kurang serius karena hukuman yang diberikan kepada pelaku dirasa masih terlalu ringan. Bahkan untuk penanganan kasus perkosaan massal yang terjadi pada bulan Mei 1998 pada masa peralihan kepemimpinan di Indonesia masih belum jelas arahnya. Meskipun berbagai pihak, termasuk pihak luar negeri telah memberi tekanan yang besar untuk penanganan terhadap masalah tersebut. Akibat belum adanya penanganan yang tuntas serta hukuman yang “cukup adil” bagi para pelaku, peristiwa perkosaan makin membuat perempuan mengalami ketakutan dan ketidaktentraman.
Budaya patriarki sebagai budaya yang berpusat pada “nilai laki-laki” merupakan basis bagi suburnya perilaku bias jender (Bhasin, 1996: 1). Perilaku tersebut, pada gilirannya, menempatkan perempuan pada posisi yang subordinatif dan marginal dan oleh karenanya dapat dikendalikan. Pengendalian tersebut dapat berupa pembatasan ruang sosial (social space), penetapan posisi dan perilaku. Budaya patriarki yang berbasis pada relasi jender lebih banyak terjadi di sektor domestik dan mendapatkan perluasan jangkauan di sektor publik manakala akses kaum perempuan juga terbuka. Pada batas tertentu, kekerasan akan muncul manakala timbul suatu anggapan bahwa perempuan melampaui “batas pengendalian” kultural yang telah ditetapkan.
Kekerasan bukan hanya menjadi monopoli bagi perempuan yang berasal dari masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, namun juga terjadi pada masyarakat dengan sistem kekerabatan bilineal atau bahkan matrilineal. Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa menganut sistem kekerabatan bilineal. Walau sistem kekerabatan dirunut dari kedua garis keturunan, namun bukan berarti hak-hak perempuan “telah” sebanding dengan hak-hak laki-laki. Masyarakat Jawa pada kenyataannya masih didominasi oleh sistem patriarki yang cenderung meminggirkan posisi perempuan. Di dalam masyarakat tersebut perbedaan norma-norma yang diberlakukan bagi laki-laki dan bagi perempuan juga terlihat jelas. Perempuan umumnya memperoleh rambu-rambu yang jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Akibatnya, kedudukan dan peran laki-laki cenderung lebih dominan.
Di sisi lain, Yogyakarta telah lama menyandang predikat kota pelajar yang menjadi barometer perkembangan pendidikan di Indonesia. Jikalau pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor determinan modernitas maka dapat dikatakan bahwa rigiditas budaya, utamanya yang tidak kondusif terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan egaliter, akan terkikis. Asumsinya, semakin terpelajar suatu masyarakat makin tinggi kesadaran dan penghargaan terhadap orang lain, termasuk terhadap kaum perempuan. Berangkat dari kompleksitas dari kondisi di atas, maka dilakukan suatu penelitian untuk mempetakan serta mengidentifikasi masalah kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta.[]
*Klik untuk mengunduh makalah: Seminar Bulanan S.297 – Susi Eja Yuarsi | 23 November 2000