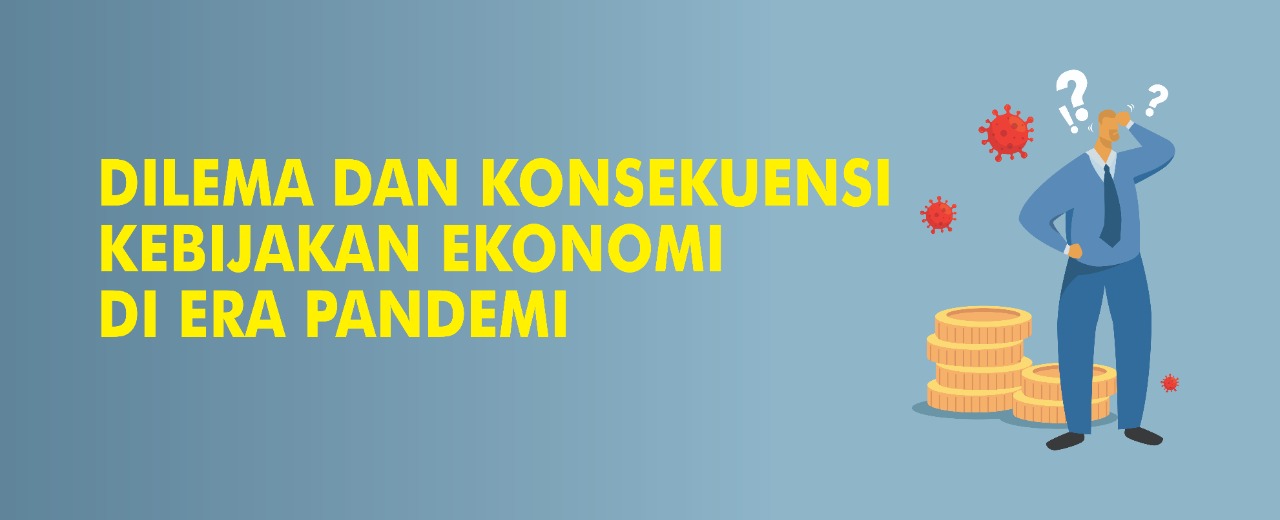Yogyakarta, PSKK UGM – Pandemi Covid-19 yang pertama kali muncul di Wuhan pada penghujung tahun 2019 dan belum dapat dipastikan kapan akan berakhir ini telah memberikan dampak pada berbagai aspek. Tidak hanya memukul sektor kesehatan, Covid-19 juga telah mengoyak perekonomian di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Pada Triwulan IV 2019, pertumbuhan Produk Domestik Bruto/PDB (Y-on-Y) masih berada di angka 4,97. Kemudian pada Triwulan I 2020, yaitu pada masa awal Covid-19 menyerang Indonesia, PDB (Y-on-Y) turun menjadi 2,97, meski masih menunjukkan angka positif. Pada perkembangan terakhir, PDB (Y-on-Y) pada Triwulan II 2020 telah terkontraksi menjadi -5,32 (Berita Resmi Statistik No. 64/08/Th.XXIII, 5 Agustus 2020).
Berdasarkan lapangan usaha, sektor pertanian adalah satu-satunya sektor yang masih memiliki pertumbuhan positif. Sedangkan berdasarkan pengeluaran, semua jenis pengeluaran mengalami kontraksi. Impor dan ekspor menjadi sektor pengeluaran yang mengalami kontraksi paling dalam, masing-masing -16,96% dan -11,66%. Guncangan ekonomi karena pandemi Covid-19 yang melanda hampir semua negara di dunia ini telah berdampak pada turunnya harga sejumlah komoditas ekspor dan lesunya perekonomian global.
Pengeluaran dari sisi konsumsi pemerintah pada Triwulan II 2020 terkontraksi menjadi -6,90. Hal ini disebabkan oleh serapan belanja anggaran yang berjalan lambat. Sampai Agustus 2020, realisasi belanja anggaran baru mencapai 48%. Tiga kementerian dengan penyerapan anggaran paling rendah adalah Kementerian Perhubungan (34,3%), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (41,5%), dan Kementerian Kesehatan (43,6%). Hal tersebut membuat Presiden Joko Widodo memberikan teguran keras kepada semua kementerian untuk mempercepat penyerapan anggaran dengan lebih efektif.
Seiring dengan diberlakukannya era kenormalan baru dan pengendoran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sejumlah kementerian kembali melakukan kegiatan perjalanan dinas ke daerah-daerah. Kegiatan ini memang dilakukan secara rutin setiap tahun oleh kementerian. Namun dengan kondisi pandemi yang belum dapat dikendalikan, bahkan tren penambahan kasus pun meningkat, rasanya kurang bijak untuk banyak melakukan perjalanan dinas. Apalagi jika tujuannya hanya untuk mempercepat serapan anggaran. Selain kontradiktif dengan upaya memutus mata rantai virus, tindakan ini juga menjadi contoh yang kurang baik bagi masyarakat dalam menyikapi pandemi yang tak kunjung selesai.
Alih-alih melakukan banyak perjalanan dinas, sebagian biaya perjalanan dinas bisa dialihkan ke program-program yang dapat mendongkrak konsumsi rumah tangga yang mengalami kontraksi menjadi -5,51% pada Triwulan II 2020. Memang benar, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga, seperti 1) perluasan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimaksimalkan menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM); 2) perubahan durasi penyaluran PKH menjadi per bulan; 3) kenaikan besaran manfaat PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); 4) subsidi biaya listrik; 5) program Kartu Pra Kerja, dan sebagainya.
Dalam jangka pendek, program-program tersebut memang membantu menjaga konsumsi rumah tangga. Namun dalam jangka panjang, bahkan setelah pandemi berlalu, akan ada persoalan yang harus diantisipasi, yaitu melebarnya ketimpangan dalam masyarakat. Masyarakat menengah ke atas memang mengalami penurunan konsumsi, tapi sifatnya lebih sementara. Selain itu, aset-aset finansial mereka justru tertolong karena saat ini aset dalam dolar memberikan imbal hasil yang bagus, harga emas naik, dan tabungan dalam mata uang asing meningkat sebagai akibat melemahnya rupiah.
Ringkasnya, kelompok masyarakat menengah ke atas berada dalam kondisi ekonomi yang stabil dan diuntungkan oleh situasi pada saat ini. Sebaliknya, kelompok masyarakat menengah ke bawah mengalami penurunan konsumsi sebagai konsekuensi dari berkurangnya atau hilangnya pendapatan akibat adanya pembatasan kegiatan. Apalagi sebagian dari mereka juga merupakan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terdampak oleh upaya efisiensi yang dilakukan perusahan setelah aktivitas ekonomi tidak dapat berjalan optimal. Dengan kata lain, mereka adalah kelompok rentan yang menjadi semakin miskin jika aktivitas ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja tidak segera kembali normal.
Pemerintah memang menghadapi dilema besar dalam mengatasi pandemi dan menyelamatkan perekonomian. Tahun ini saja, negara Indonesia tercatat mengalami defisit Rp 1.039 triliun. Bank Indonesia (BI), seperti halnya bank-bank sentral di negara lain, juga mengalami dilema, yaitu membantu pemerintah mendorong ekonomi atau menjaga kurs rupiah agar tidak terus melemah.
Selama ini, kurs rupiah yang kuat dikombinasi suku bunga atau imbal hasil yang tinggi serta menjadi modal untuk menarik dana portofolio dari luar. Suka atau tidak suka, hal ini membantu menopang devisa negara dan mempersempit defisit neraca transaksi berjalan, bahkan sebelum terjadinya pandemi. Namun menjaga suku bunga tetap tinggi tidak akan menolong pelaku usaha dalam negeri yang saat ini sedang mengalami kelesuan. Untuk menggairahkan kembali ekonomi dalam negeri, suku bunga harus diturunkan, sehingga biaya bunga perbankan juga lebih rendah.
Secara keseluruhan, biaya modal yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha juga menjadi lebih murah, sehingga aktivitas ekonomi dapat lebih bergeliat dan lapangan pekerjaan akan semakin terbuka. Pilihan inilah yang diambil oleh BI. Dengan cara menurunkan suku bunga dari sekitar 5% menjadi 4% per Juli 2020, pemerintah mampu mendorong ekonomi semakin kuat. Kesediaan BI membantu pemerintah ini juga mampu mengurangi defisit melalui mekanisme pembagian beban (burden sharing) pada tahun ini.
Dengan membeli obligasi pemerintah di pasar perdana senilai Rp 397 triliun, pemerintah tidak perlu repot menjual obligasi ke pasar dan bisa membayar bunga lebih rendah. Kebijakan ini beresiko tinggi, karena artinya 1) BI akan mencetak likuiditas rupiah baru untuk pemerintah yang akan membuat kurs rupiah semakin melemah, dan 2) independensi BI sebagai regulator moneter semakin berkurang. Pada akhirnya, kedua hal ini akan mengurangi minat investor asing untuk menanamkan portofolionya di Indonesia.
Bagaimanapun, pilihan telah diambil. Pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan pilihan tersebut beserta konsekuensi yang mungkin terjadi. Untuk sementara, investasi asing mungkin tidak akan bisa terlalu diharapkan karena suku bunga yang rendah. Secara praktis, ekonomi dalam negeri harus lebih digenjot. Likuiditas baru (uang baru) yang dicetak oleh BI sebesar Rp 397 triliun dari hasil mekanisme burden sharing harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh pemerintah.
Program-program pemerintah, terutama program pemulihan ekonomi nasional yang dibiayai dari likuiditas tersebut, harus benar-benar dilakukan secara efektif agar dapat memperbaiki ekonomi masyarakat dan negara. Jangan sampai likuiditas ini sia-sia dan mendatangkan masalah baru di masa mendatang. Ke depan, jika ingin menjaga kepercayaan publik global agar mau menanamkan investasi di Indonesia, maka pemerintah perlu mempertimbangkan ulang rencananya untuk 1) meminta bantuan pembiayaan dari BI hingga tahun 2022 dan 2) merevisi beberapa regulasi yang berpotensi memangkas wewenang dan independensi BI.
Kenyataannya, publik global merasa was-was untuk menanamkan portofolionya di Indonesia, karena penanganan Covid-19 di Indonesia dinilai belum baik, serta adanya kebijakan burden sharing oleh pemerintah dan BI. Rasa was-was tersebut seharusnya tidak ditambah dengan isu meresahkan mengenai rencana pembiayaan BI hingga tahun 2022 dan revisi regulasi BI. Meski belum pasti akan dilakukan, dampak terhadap Indonesia di mata perekonomian global harus benar-benar diperhitungkan.
*Dyah Kartika, S.Si, M.Ec.Dev | Asisten Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM | Ilustrasi: M. Affen Irhandi/PSKK UGM