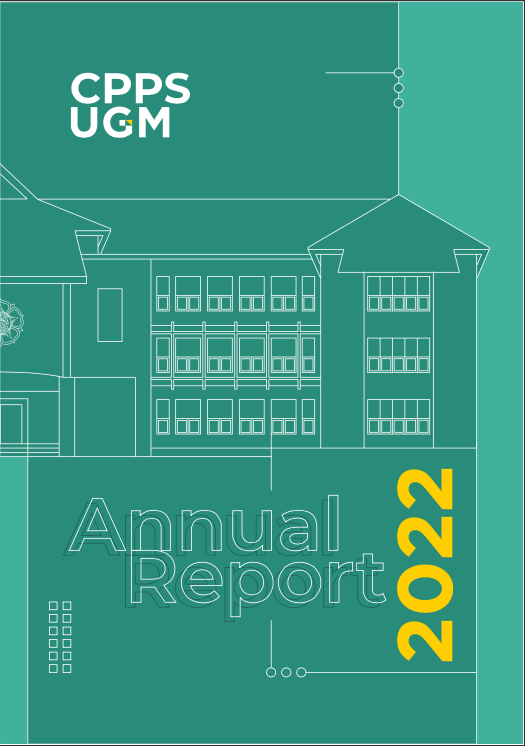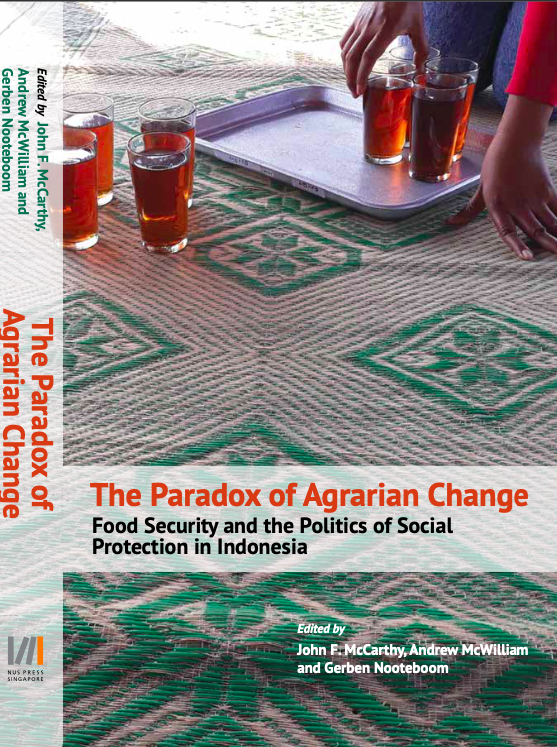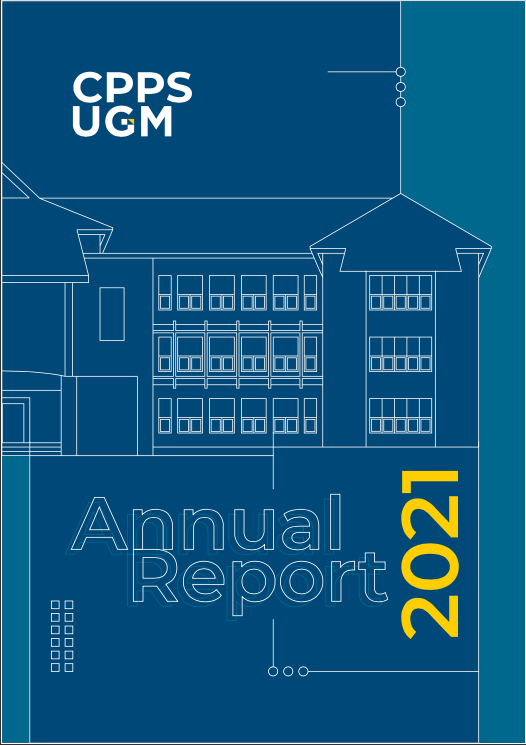SUNAT PEREMPUAN: Indonesia Masuk Pantauan Radar FGM/C Global
|Berita PSKK, Kegiatan, Main Slide, Media, Pelatihan / Lokakarya

Yogyakarta, PSKK UGM – Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan, secara nasional, persentase pernah disunat pada anak perempuan usia 0-11 tahun sebesar 51,2 persen. Hasil ini cukup menimbulkan kegemparan. Indonesia yang selama ini tidak ada di dalam “pantauan radar” sunat perempuan (female genital mutilation/cutting) di tingkat global, kini tiba-tiba muncul.
Hal itu disampaikan oleh Richard Makalew, Penanggungjawab Program Kependudukan dan Pembangunan, Dana Kependudukan PBB (UNFPA) Indonesia saat pelatihan asisten lapangan “Survei Medikalisasi Sunat Perempuan di Indonesia 2017” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada di Hotel Galuh Prambanan beberapa waktu lalu.
Selama ini praktik sunat perempuan dinilai sebagai African phenomenon, fenomena yang hanya terjadi di Afrika. Namun, data Riskesdas 2013 yang dijadikan referensi dalam laporan Badan PBB untuk Anak-Anak (UNICEF) di tingkat global kemudian memunculkan pandangan yang lain. Bahwa sunat perempuan bukan hanya fenomena di Afrika. Praktik sunat perempuan juga terjadi di Asia, khususnya Indonesia.
Richard mengatakan, UNFPA sebagai lembaga PBB yang bergerak di bidang kependudukan, kesehatan reproduksi, gender, dan remaja tertarik untuk mengetahui lebih lanjut laporan tersebut. Bekerjasama dengan PSKK UGM dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), UNFPA Indonesia melakukan studi tentang sunat perempuan di Indonesia.
“Kita ingin melihat lebih dalam. Persentase 51,2 itu merupakan praktik sunat perempuan yang seperti apa? Siapa yang melakukan tindak medikalisasi tersebut? Selama ini, bayangan kita, sunat perempuan di Indonesia hanyalah simbolis karena terkait tradisi, tidak sampai pada praktik-praktik yang membahayakan,” jelas Richard.
Data Riskesdas 2013 yang diluncurkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan menunjukkan, ada 20 provinsi yang memiliki persentase sunat perempuan di atas rata-rata nasional. Tertinggi adalah Gorontalo dengan persentase sunat perempuan mencapai 83,7 persen, disusul kemudian Bangka Belitung, Banten, Kalimantan Selatan, dan Riau.
Sementara jika dilihat dari karakter wilayah, persentase pernah disunat pada anak perempuan usia 0-11 tahun di perkotaan sebesar 55,8 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan di perdesaan, yakni 46,9 persen.
Peneliti PSKK UGM yang juga pemerhati isu-isu gender dan kesehatan reproduksi, Dr. Dewi Haryani Susilastuti mengatakan, studi yang dilakukan ini bukanlah replikasi dari Riskesdas. Studi ini bertujuan untuk membantu pemerintah di dalam mengambil kebijakan tentang sunat perempuan. Evidence-based policy agar kebijakan yang diambil tersebut berdasarkan basis data yang bisa dipertanggungjawabkan.
Hendak melihat lebih dalam tentang praktik medikalisasi sunat perempuan, maka ada beberapa pertanyaan yang akan dicari tahu jawabannya melalui studi ini, tambah Dewi. Misalnya, siapa dan bagaimana karakter klien yang mempraktikkan sunat perempuan? Apa alasan mereka melakukan praktik sunat perempuan? Kemudian siapa penyedia layanan sunat perempuan? Dimana dan bagaimana cara penyedia layanan ini melakukan praktik sunat perempuan? Bagaimana sikap dan pengetahuan penyedia layanan kesehatan (dokter, bidan, perawat) tentang sunat perempuan? Apakah ada insentif bagi penyedia layanan kesehatan untuk melakukan sunat perempuan?
Studi ini akan dilakukan di tujuh provinsi dengan prevalensi sunat perempuan tertinggi di Indonesia, antara lain Gorontalo, Banga Belitung, Banten, Riau, Kalimantan Selatan, Jawa Barat. Sulawesi Barat. Ditambah, tiga provinsi yang memiliki peraturan daerah yang mendukung praktik medikalisasi perempuan di fasilitas pelayanan kesehatan, yakni Kalimantan Timur, Jambi, dan Nusa Tenggara Barat.
“Ini sangat menarik sekaligus memprihatinkan jika dilihat dari perspektif kebijakan. Mengapa? Karena sunat perempuan merupakan praktik yang seharusnya dihilangkan. Ini justru diatur oleh pemerintah setempat guna pendapatan daerah atau retribusi,” kata Dewi.
Dari sisi kebijakan, peraturan tentang sunat perempuan juga mengalami pasang surut. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat pernah mengeluarkan surat edaran tentang larangan medikalisasi sunat perempuan bagi petugas kesehatan. Namun di penghujung 2008 terjadi protes dan penolakan Majelis Ulama Indonesia terhadap surat edaran tersebut.
Perbedaan pendapat ini kemudian disikapi Kemenkes dengan mengeluarkan Permenkes No. 1636/MENKES/XI/2010 tentang Sunat Perempuan. Bukannya menegaskan pelarangan pelukaan terhadap genital perempuan, peraturan ini justru menjadi petunjuk pelaksanaan bagi tenaga kesehatan untuk melakukan sunat perempuan.
Di dalam peraturan itu sebenarnya juga diatur bahwa setiap pelaksanaan sunat perempuan hanya dilakukan atas permintaan dan persetujuan perempuan yang disunat, orang tua, dan/atau walinya. Tapi praktiknya tidak demikian, tambah Dewi. Ada paket melahirkan, tindik, dan sunat yang disediakan oleh beberapa layanan kesehatan.
“Orang tua tidak ditanya, tiba-tiba bayinya diantar oleh bidan dan dikatakan bayinya sudah cantik, sudah ditindik dan disunat. Satu paket, tidak ditanya. Padahal dalam aturannya jelas bahwa setiap pelaksanaan sunat perempuan harus diinformasikan kemungkinan terjadi pendarahan, infeksi, dan rasa nyeri. Praktiknya, tidak diberitahu,” kata Dewi lagi.
Saat ini, permenkes tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak lagi berlaku melalui Permenkes Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan ini juga memberikan mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara’k untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat serta tidak melakukan mutilasi pada genital perempuan. [] Media Center PSKK UGM | Photo: Tradisi sunat perempuan di Gorontalo (AFP Photo/Bayu Ismoyo): CNN Indonesia