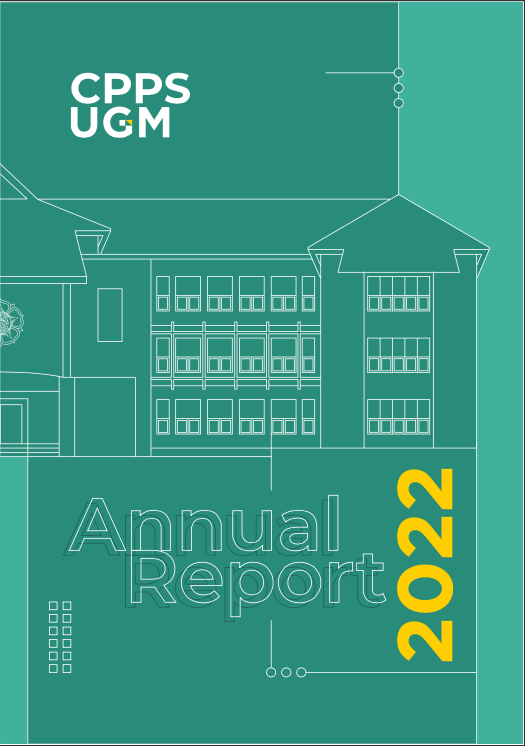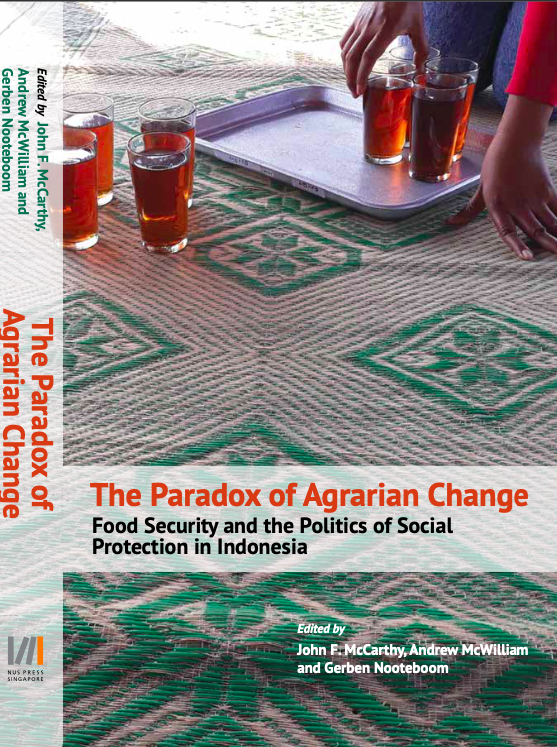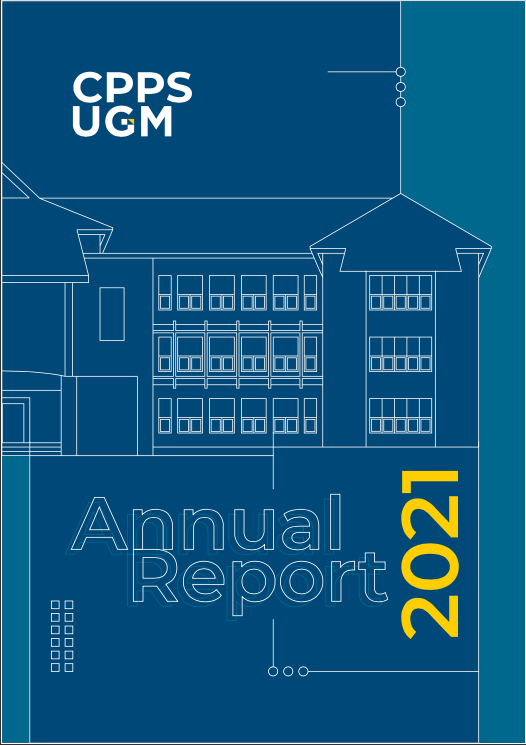Meneguhkan Teologi Keislaman-Keindonesiaan di Era Kebangkitan Agama | Oleh: Hakimul Ikhwan
|Berita PSKK, Esai & Opini, Main Slide, Media

Era ini disebut sebagai era kebangkitan agama. Agama yang semula diprediksi oleh banyak ilmuwan sosial akan mengalami kebangkrutan seiring dengan perkembangan modernisasi dan industrialisasi, ternyata justru tampil menjadi elemen yang maha penting. Agama—simbol, ajaran, lembaga—hadir dan merasuk ke dalam semua sendi kehidupan masyarakat Abad ke-21.
Bahkan, generasi milenial yang paling terpapar teknologi informasi dan komunikasi digital menjadi agen utama yang memunculkan narasi-narasi agama di ruang publik. Seorang aktivis muslim yang sudah sangat senior mengatakan bahwa para mahasiswa di kampus hari ini lebih khusyuk shalatnya dibandingkan para aktivis pada zamannya. Grup Sabyan, yang terdiri para seniman usia sangat muda, dengan sangat fasih menyanyikan Deen Assalam yang menggema dimana-mana, warung makan, mall, dan kafe. Dan, Dodi Hidayatullah yang sangat apik mengubah lirik Despacito—yang dianggap moral-less dan dilarang di Malaysia karena alasan tersebut—menjadi lagu yang sarat simbolisme dan ajaran Islam. Dalam bentuk yang lebih ekstrim, kelompok muda melahirkan gelombang pengikut ISIS di Eropa. Mereka secara diam-diam dan terorganisir berhasil menyeberang batas-batas teritorial negara untuk bergabung menjadi pasukan militer ISIS.
Telah menjadi tanda-tanda zaman bahwa ghirah keislaman—juga kekristenan, kebuddhaan, keyahudian—semakin meningkat. Di kalangan umat Islam, meluas kesadaran untuk menjadi muslim yang kaffah, muslim yang seutuhnya. Di kalangan profesional, untuk menjadi muslim seutuhnya mereka memutuskan untuk tidak menggunakan bank konvensional dan beralih ke bank sharia. Di kalangan muda terdidik, tidak sedikit mereka yang dengan kesadaran penuh memilih jalan hidup berdagang. Jenis pekerjaan ini, dalam pandangan mereka, adalah pekerjaan yang paling disukai Nabi Muhammad. Tidak sedikit mereka yang ‘berhijrah’ keluar dari lembaga-lembaga pemerintah, sebagai abdi negara, atau karyawan swasta untuk meraih kehidupan yang ‘lebih berkah’. Maka, label ‘halal’ menjadi rujukan utama masyarakat muslim hari ini dalam membeli produk. Label halal tidak hanya berlaku untuk produk makanan, minuman, dan kosmetik tetapi juga produk-produk lain seperti kulkas dan jilbab.
Gairah umat Islam untuk menjadi muslim yang kaffah juga ditunjukkan dengan gelombang besar travel umrah dan haji. Saat ini, salah satu bisnis yang digemari adalah travel haji dan umrah karena pasarnya yang selalu tinggi, apalagi di musim-musim tertentu seperti Ramadhan dan Tahun Baru. Skandal First Travel dan Abu Tour sepertinya tidak mempengaruhi bisnis ini. Agen travel berlomba memikat jamaah, baik melalui penawaran harga tiket murah maupun kerjasama dengan artis selebriti atau ustad selebriti.
Menutup aurat sudah menjadi hal yang biasa dan terlalu mainstream di kalangan muslimah. Oleh karenanya, proses hijrah untuk menjadi muslimah yang kaffah terus bergerak ke kanan melalui komunitas hijabers, bahkan sekarang berkembang niqobers. Kalau sebelumnya para niqobers tidak pernah mengunggah foto atau selfie, niqobers zaman sekarang menggunakan media sosial, dengan unggahan foto, modifikasi niqob, sembari tetap sharing tausiah.
Sayangnya, keinginan yang kuat untuk menjadi muslim yang kaffah seringkali berbenturan dengan keharusan menjadi manusia Indonesia yang kaffah. Keharusan menjadi warga negara yang kaffah. Dalam derajat yang ekstrim, menjadi muslim yang kaffah ditandai dengan keinginan untuk berhukum dengan Hukum Allah. Hukum selain Allah dianggap sesat. Kekuasaan selain Allah adalah adalah thoghut.
Umat Islam Indonesia hari ini dihadapkan pada persoalan serius mempertemukan kembali spirit keislaman dan ke-Indonesia-an. Pertanyaannya, bisakah menjadi muslim yang kaffah sekaligus juga menjadi warga Indonesia yang kaffah, yang baik, yang Pancasilais?
Setiap generasi memiliki tantangannya masing-masing. Tidak terkecuali generasi kita. Tantangan generasi ini tidak lebih mudah dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Tetapi juga tidak lebih sulit dari generasi sebelumnya.
Sesungguhnya, kalau kita memahami Islam dan berbagai ekspresi keislaman dalam beragam bentuk pemahaman doktrin, ayat dan teks, serta praktek-praktek keislaman, maka kita akan menemukan kenyataan bahwa Islam tidaklah tunggal. Islam hadir dan diekspresikan dalam beragam interpreasi paham keagamaan, teks dan doktrin, bahkan praktek-praktek keseharian yang berbeda-beda antara komunitas, masyarakat, negara dan bangsa, bahkan antarperiode.
Sejak era paling awal sekali dalam sejarah Islam, telah terjadi perpecahan pemahaman keagamaan terhadap teks dan ilmu kalam. Ini melahirkan perbedaan kelompok pandangan teologis, misalnya antara As’ariay dan Mu’tazilah, Qodariyah dan Jabariyah, serta Maturudiyah. Dalam perdebatan ilmu kalam atau ilmu tauhid, terjadi perdebatan apakah Al-Quran adalah kholiq atau makhluq? Fakta-fakta sejarah ini menghadirkan kepada kita bahwa dalam hal-hal fundamental, teologis, Islam tidaklah satu. Ada banyak pandangan teologis yang berbeda.
Jika dalam hal teologis saja Islam tidak tunggal apalagi dalam hal-hal ibadah dan mu’amalah. Dalam hal shalat misalnya, kita memaklumi ada banyak sekali yang berbeda mulai dari bacaan shalat antara “wajjahtu wajhiya” dan “allahumma baa’id baini”, “sedekap tangan”, dan lain-lain. Tata cara berwudhu pun berbeda-beda antara para imam mazhab.
Singkat kata, dari lima rukun Islam, yang tunggal dan fix adalah mengucapkan kalimat “laa ilaha illallah, muhammadur rasulullah”. Selebihnya terjadi perbedaan.
Jika dalam ibadah saja Islam hadir dalam beragam bentuk ekspresi, apalagi dalam hal mu’amalah.
Kita dapat membedakan dari jilbab, atau tutup kepala muslimah, mana yang Indonesia, Malaysia, Pakistan, atau Bangladesh. Bahkan, jubah yang dipakai oleh laki-laki muslim bisa dibedakan antara jubah Madinah atau jubah Yaman.
Yang manakah yang Islam dan tidak Islam? Atau, lebih Islam dibandingkan yang lain? Dalam keberagaman tersebut kita menemukan kekayaan tradisi keislaman. Tetapi, keberagamaan tersebut dapat menjadi bencana jika terjadi klaim bahwa yang satu lebih Islam dari yang lain.
Pertanyaan berikutnya, adakah tradisi atau praktek keagamaan Islam yang universal? Jawabnya, ada, yaitu dalam hal ucapan ‘kalimat tauhid,’ jumlah rakaat shalat wajib, puasa di Bulan Ramadhan, dan Haji pada bulan Haji. Tetapi dalam prakteknya, sebagaimana disebutkan di atas, terjadi perbedaan dalam hal pelaksanaan shalat, puasa, dan haji.
Dari uraian di atas kita dapat menarik kesimpulan. Menjadi muslim yang kaffah tidak bisa membuat kita terbebas atau terlepas dari partikularitas-partikularitas praktek-praktek keagamaan. Menjadi muslim yang kaffah artinya mengamalkan keislaman secara sungguh-sungguh dan konsisten di dalam garis metodologi keislaman tertentu yang tetap saja partikular. Menjadi muslim yang kaffah artinya ber-Islam secara kaffah dalam versi metodologis tertentu, yang belum tentu lebih Islam dibandingkan versi metodologis yang lain.
Mengapa kesimpulan pertama tersebut sulit diterima—terutama di sebagian kalangan muslim? Jawabnya, karena dalam mindset umat muslim Indonesia, bahkan dunia, keberagaman praktek keagamaan tersebut tidak hadir dalam ruang vakum, melainkan dikonstruksikan dalam relasi kuasa (power relation). Dalam relasi kuasa inilah, suatu praktek keagamaan tertentu asosiatif dengan entitas kelompok tertentu. Slametan asosiatif dengan praktek masyarakat Jawa atau Melayu. Haflah tasyakuran asosiatif dengan masyarakat Arab. Gamelan identik dengan Jawa. Gambus identik dengan Timur Tengah.
Dalam relasi kuasa tersebut maka slametan tidak bisa disetarakan dengan haflah tasyakuran. Gamelan tidak setara dengan gambus. Karena, dalam relasi kuasa, Jawa dan Melayu tidak setara dengan Arab dan Timur Tengah. Relasi kuasa mengandaikan suatu entitas masyarakat atau golongan lebih memiliki kuasa, lebih mulia, dan terhormat, dibandingkan entitas masyarakat atau golongan lain. Konstruksi tersebut berlangsung dalam rentang sejarah yang panjang dan dilakukan oleh pihak-pihak yang ‘lebih berkuasa’ atau otoritatif. Konstruksi tersebut dibangun dalam relasi kolonialistik.
Sudah sangat lama sekali dunia ini dibagi ke dalam dua kutub, yakni Kutub Barat dan Kutub Timur. Pembagian ini diperlukan oleh pihak berkuasa—para kolonial—untuk membangun konstruksi identitas bahwa Barat (penguasa/kolonial) lebih berkuasa, lebih mulia, lebih terhormat, lebih beradab. Karena itu, kata Edwar Said, konstruksi Timur dan Barat bukan hanya soal pembagian dunia tetapi juga sekaligus instrumen penjajahan. Timur dan Barat sebagai konstruksi identitas yang melanggengkan penjajahan. Paling tidak, konstruksi tersebut untuk mengkonstruksi perbedaan ‘kuasa’.
Ketimpangan relasi kuasa tidak hanya terjadi dalam konstruksi Timur dan Barat dalam dunia global. Tetapi juga terjadi dalam pemilahan dunia Islam. Arab dan Timur Tengah menjadi representasi “Barat yang maju dan terhormat”, dan non-Arab (termasuk Melayu, Bangladesh, India Muslim, China Muslim, dsb) menjadi representasi “Timur yang ‘kelas dua’ dan kurang Islam”. Dalam ketimpangan relasi kuasa ini, maka yang “Timur (non-Arab)” berusaha menjadi “Barat (Arab)” dalam berbagai ekspresi keagamaan dan kebudayaan. Bahkan, tidak sedikit orang Timur (non-Arab) berperilaku melebihi yang Barat (Arab). Maka, menjamurlah penggunaan jubah, turban, dan istilah-istilah Arab, termasuk lagu-lagu Arab.
Dengan demikian, kesimpulan kedua, preferensi praktek-praktek dan simbolisme keagamaan tertentu yang seolah-olah lebih utama, mulia, dan terhormat adalah akibat pengaruh cara pandangan kolonialistik yang melihat dunia dalam relasi relasi kuasa yang tidak setara. Suatu praktek dan ekspresi kebudayaan secara ontologis dan epistemologis tidaklah lebih mulia dari yang lain.
Spirit kenabian Muhammad SAW justru ingin menghancurkan cara pandang kolonialistik tersebut. Ketika saat itu, suku-suku Arab, termasuk Quraisy, merasa lebih mulia dari yang lain, maka cara pandang tersebut secara revolusioner dihancurkan oleh Nabi Muhammad dengan mengatakan “Laa Fadla Li Arabiyin ‘ala ‘Ajamiyin, wa laa kinnal fadhla bittaqwa.”
Dari dua argumentasi di atas, yaitu (1) menjadi muslim yang kaffah tidak berarti terbebas dari partikularitas paham dan praktek keagamaan Islam, dan (2) pengaruh relasi kuasa yang timpang membuat suatu praktek dan simbolisme lebih utama dan mulia, dan (3) spirit kenabian yang mendobrak rasisme dan chauvinisme materialistik, maka kita dapat membangun argumentasi bahwa (4) tidak ada jurang pemisah antara keislaman dan keindonesiaan.
Untuk poin terakhir ini, saya ingin mengelaborasi rumusan Al-Quran, yang sekaligus basis teologis untuk mempertemukan atau mengawinkan antara keislaman dan keindonesiaan.
Allah SWT berfirman dalam QS Ibrahim 24-26.
Artinya: “Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.”
“Kalimat toyyibah” dalam ayat tersebut dijelaskan oleh para ulama adalah kalimat tauhid atau seruan kepada keimanan kepada Allah SWT. Tetapi, secara umum, kalimat thoyyibah berarti kalimat yang baik, yaitu segala bentuk ajakan kepada kebaikan.
Ayat tersebut memberikan kriteria kalimah thayyibah, yaitu mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat. Memiliki kesadaran sosiologis, kesadaran akan konteks struktural dan kultural dimana “kalimat toyyibah” tersebut disampaikan. Dalam hal ini maka pemahaman akan konteks (sosiologis/kekinian, dan historis/rentang waktu) menjadi sangat penting.
Ada banyak contoh, ‘itibar’, dari Al-Quran dan Sirah Nabawiyah yang menekankan pentingnya kesadaran kontekstual (sosiologis-historis). Misalnya, tidak ada hambatan bagi Allah untuk langsung memperjalankan Nabi Muhammad untuk bermiraj ke sidratul muntaha. Tetapi, karena perjalanan tersebut bukanlah perjalanan individual melainkan mengandung misi keumatan bagi umat manusia maka Nabi Muhammad diperjalankan dalam isra’ ke Baitul Maqdis untuk dapat diuji kebenarannya dalam nalar manusia. Tidak ada hambatan Allah untuk menjadikan Nabi Muhammad dari suku mana pun, tetapi karena dalam tradisi Arab saat itu terdapat stratifikasi suku, maka akan lebih mudah dan dapat diterima kenabian yang berasal dari suku Quraish yang terhormat. Bahkan, Nabi Muhammad pun harus berdarah-darah dalam peperangan, gigi beliau patah, karena dengan begitu maka legitimasi kepemimpinan beliau menjadi semakin kuat. Atau, Sayyidina Ali pada akhirnya kalah berperang melawan Mu’awiyah, bukan karena keimanan Ali kurang, atau lebih rendah dari Muawiyah. Juga bukan berarti keridhaan Allah atas Mu’awiyah lebih besar dari Ali. Kekalahan tersebut karena fakta dan realita sosial Mu’awiyah berasal dari suku yang jauh lebih besar, dengan pengikut bala tentara yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan suku dan para pengikut Sayyidina Ali.
Kesadaran sosiologis juga melekat di dalamnya kesadaran historis. Karakteristik berpikir sosiologis adalah kesadaran historis, bahwa sesuatu terjadi tidak dengan sendirinya melainkan melalui proses rentang waktu yang panjang hasil dari pergulatan berbagai elemen sosial.
Ayat tersebut menggunakan kata “syajaroh” yang dalam bahasa Indonesia disebut pohon, tetapi juga bisa diterjemahkan sebagai ‘sejarah’. Sejarah atau silsilah keluarga juga dalam bahasa Arab disebut sebagai ‘syajaroh’. Karenanya, misi tauhid harus memenuhi prasyarat kesadaran akan sejarah, baik sejarah diri, keluarga, komunitas, masyarakat, dan bangsa.
Dengan perumpamaan “syajaroh” tadi maka keimanan menjadi kokoh, akarnya kokoh menghujam (ashluha tsaabit) dan cabang-cabangnya atau manfaat dan buah dari kebaikan tersebut menjulang tinggi (ke langit).
Sebaliknya, perkataan atau perbuatan yang buruk, yang tidak memiliki kesadaran sosiologis dan historis, seperti pohon yang buruk yang akarnya tercerabut dari tanah (permukaan bumi) dan tidak dapat tegak sedikit pun.
Perumpamaan umat yang tidak memiliki kesadaran sosiologis historis, maka tidak memiliki pegangan dan menjadi mudah terombang-ambing dalam arus diskursus yang datang entah dari mana. Ketika agenda global anti terorisme, maka dia terombang-ambing dalam diskursus tersebut. Terbawa untuk menjadi bagian dari terorisme ATAU menjadi orang yang dihantui ketakutan oleh diskursus terorisme. Hal yang sama juga terjadi pada gelombang Anti-Ahmadiyah, Anti-Syiah, ISIS, dan sebagainya. Kesimpulannya, untuk tidak terombang-ambing, jadilah seperti pohon yang menghujam ke bumi. Menjadi seorang muslim yang punya kesadaran sosiologis dan historis.
Selamat Hari Pancasila.
Selamat berikhtiar menjadi muslim yang kaffah, sekaligus warga Indonesia Pancasilais yang kaffah. [] Hakimul Ikhwan, Ph.D. (Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Dosen Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM)
*Foto aksi Pancasila/pinterpolitik.com