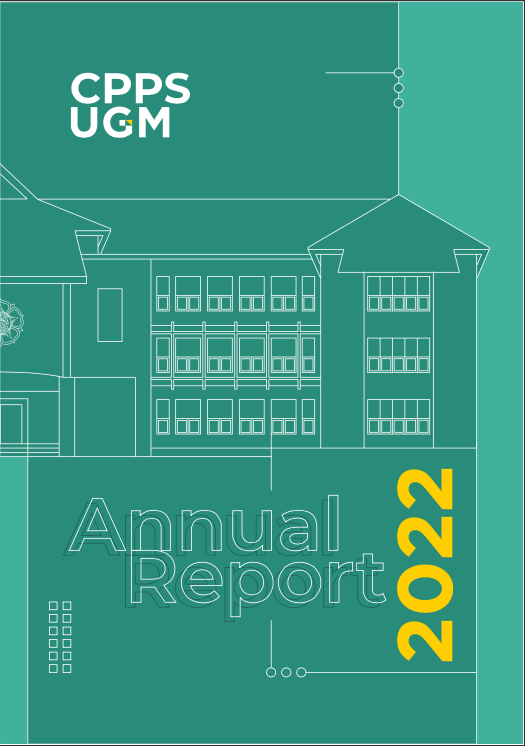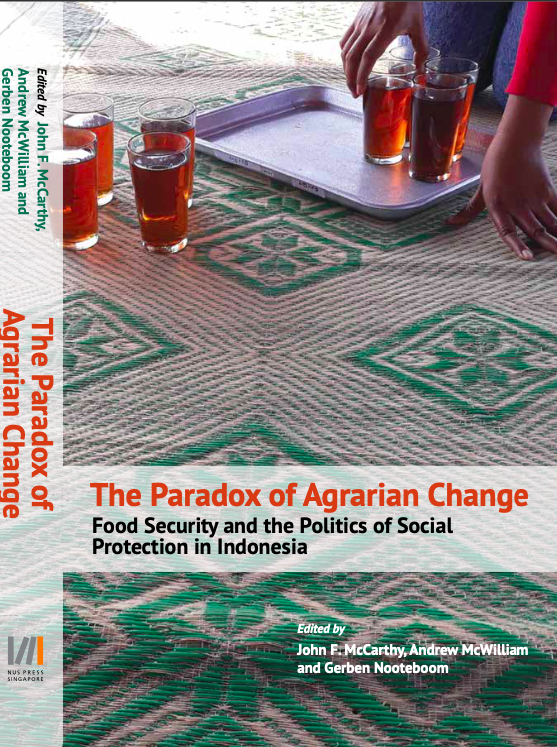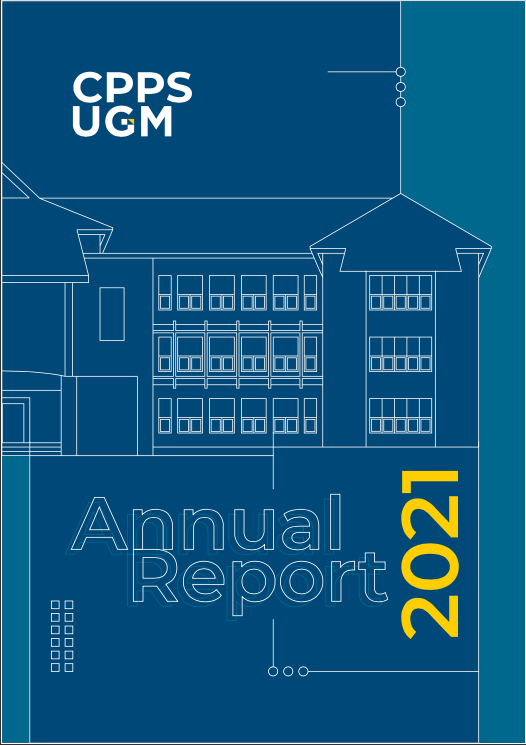Collaborative Governance dan Penurunan Kemiskinan | Oleh: Agus Heruanto Hadna
|Esai & Opini, Media

Harian Jogja – Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencanangkan target bahwa pada 2019 angka kemiskinan di Indonesia berada pada kisaran 7 hingga 8 persen. Sedangkan angka gini rasio diproyeksikan akan turun menjadi 0.36 di tahun yang sama. Pertanyaannya, apakah angka-angka optimis ini bisa dicapai pada 2019? Mengingat. masih ada permasalahan mendasar dalam tata kelola program pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Pemerintah pusat memiliki sejumlah program untuk menurunkan angka kemiskinan, antara lain Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), bantuan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan program-program lainnya yang tersebar di sejumlah kementerian. Belum lagi, program-program penanggulangan kemiskinan di daerah baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota.
Fakta ini menunjukkan, pemerintah sebetulnya tidak kekurangan program guna menekan angka kemiskinan. Namun, mengapa angka kemiskinan di 2015 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) masih bertengger di angka 11,22 persen atau sebanyak 28,59 juta orang? Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan semester sebelumnya (September 2014), yakni 27,73 juta orang atau 10,96 persen. Indeks gini rasio juga menunjukkan tren kenaikan, yakni 0.41 pada 2015 dibandingkan dengan indeks sebelumnya 0.31 pada 1999. Banyak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah menerima bantuan, namun masih hidup miskin dan justru bergantung pada bantuan pemerintah. Data tadi lalu menimbulkan keraguan akan efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang sedemikian banyak. Tulisan ini mencoba untuk menggali persoalan program penurunan angka kemiskinan, khususnya bagaimana membangun collaborative governance sehingga efektivitas program meningkat.
Collaborative governance dalam tulisan ini dimaknai sebagai bersatunya institusi publik dan pihak terkait (stakeholders) nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan melalui konsensus dan partisipasi yang hasilnya ditanggung bersama dalam pelaksanaan kebijakan atau program. Model governance ini dicirikan, antara lain adanya kesetaraan di antara stakeholders, sifat partisipatif dan menghindari tekanan politis dan administratif (konsensus), kendati struktur formal, tetap lentur dan cenderung sederhana, dan fokus terhadap penyelesaian kebijakan dan program secara lebih efektif. Model ini sangat relevan untuk mendorong efektivitas program penurunan angka kemiskinan, mengingat masih lemahnya implementasi program tersebut di lapangan.
Salah satu kelemahan implementasi program penurunan angka kemiskinan adalah sangat hirarkis atau top down. Semua program penurunan angka kemiskinan merupakan program pemerintah pusat yang diterapkan di daerah dan cenderung mengabaikan fakta-fakta keragaman kemiskinan (kemiskinan asimetris) di tingkat lokal. Beragamnya faktor penyebab kemiskinan seharusnya jadi pendorong beragamnya program. Namun, dalam logika rezim administratif, biasanya tidak terjadi karena sulit mengendalikan capaian atau output program. Program kemiskinan yang seharusnya kaya akan inovasi, pada akhirnya tenggelam oleh rutinitas rezim birokrasi. Kelemahan lain adalah terabaikannya kontekstualitas program karena tertekannya partisipasi dari mereka yang menerima manfaat (beneficiaries). Implikasinya, kinerja program untuk menekan angka kemiskinan menjadi lemah.
Kelemahan lainnya, program kemiskinan di tingkat nasional tersebar di hampir semua kementerian dan di tingkat lokal tersebar di banyak dinas. Anggaran yang disalurkan untuk program-program ini sangatlah besar, tapi energinya jadi terpecah ke dalam unit-unit kelembagaan pemerintah sehingga sangat kecil mendorong perubahan. Energi besar ini bisa disatukan, namun masih masih terhambat oleh karakter sektoral di dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Banyak program pengentasan kemiskinan yang tumpang tindih. Kegiatan maupun target sasarannya sama baik wilayah maupun individu yang disasar. Sebaliknya, ada kevakuman program karena tidak ada koordinasi dan sinkronisasi perencanaan.
Berbagai fakta di atas menunjukkan, ada persoalan pada tataran tata kelola kelembagaan untuk program pengentasan kemiskinan. Masalah berakar pada pemahaman program kemiskinan sebagai hal yang biasa (business as ussual). Memperhatikan data kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi saat ini, perlu ada terobosan kuat untuk mendorong perubahan dalam kebijakan dan program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kebijakan dan program yang terlalu biasa harus didorong menjadi kebijakan dan program yang luar biasa. Ciri yang harus dikembangkan adalah desentralisasi program diberikan kepada tingkat bawah seperti level kampung atau desa, keragaman kemiskinan diakui sebagai dasar penyusunan program, partisipatif serta menyokong kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Ini adalah bentuk collaborative governance dalam kebijakan dan program penurunan laju angka kemiskinan. Saya menggunakan frasa “perspektif kerakyatan” untuk memudahkan pemahaman di dalam mengembangkan serta menerapkan model ini.
Desentralisasi dalam desain program dan kegiatan harus berbasis di tingkat kampung atau desa karena merekalah yang memahami betul kondisi wilayah dan tingkat kemiskinan di sana. Konsep desentralisasi sesungguhnya relevan dengan upaya pemerintah untuk menurunkan dana desa. Dana ini bisa digunakan untuk membantu masyarakat dalam mendesain program serta kegiatan yang sesuai dengan permasalahan dan potensi di desa. Pemerintah tidak lalu berpangku tangan karena sesuai kewajibannya, harus menjalankan tugas regulasi, fasilitasi, dan kontrol. Pertanggungjawaban harus diberikan desa kepada komunitasnya serta pemerintah yang telah mengalokasikan anggaran.
Keragaman kemiskinan atau asymmetric poverty merupakan konsep dasar kemiskinan yang seharusnya digunakan oleh para pengambil kebijakan di dalam merumuskan kebijakan penentasan kemiskinan. Kata kunci kemiskinan asimetris adalah keragaman dan mikro. Penyebab kemiskinan begitu beragam dan kemiskinan tidak selalu dipandang dari perspektif moneter—karena tidak memiliki uang atau tidak mampu membeli kebutuhan dasar.
Kemiskinan adalah multidimensi dan salah satu parameternya adalah akses. Akses tidak hanya dipahami dalam konteks mendapatkan peluang seperti kemampuan RTSM untuk memperoleh layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Tidak kalah pentingnya adalah peluang mereka untuk sama-sama mendapatkan aset. Dalam banyak kasus mengapa kemiskinan masih saja terjadi, padahal bantuan sudah banyak diterima, karena RTSM belum memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan aset. Pada masyarakat komunal, kemampuan untuk memperoleh aset sangat mudah diperoleh sepanjang hukum adat diakui oleh hukum negara. Sementara untuk masyarakat yang tidak berbasis komunal, harus dicarikan model kebijakan yang tepat agar peluangnya sama di antara semua kelompok masyarakat.
Parameter kemiskinan berperspektif multidimensi lainnya adalah faktor-faktor modal sosial seperti gotong royong, kohesivitas, partisipasi, daya juang, gender, pengetahuan tentang alat dan sumber produksi, dan sebagainya. Beberapa kasus kemiskinan berakar dari lemahnya modal sosial. Parameter ini bisa digunakan sebagai dasar untuk mendesain program, khususnya guna membangkitkan kembali modal sosial sebagai pendorong pengentasan kemiskinan dari bawah (perspektif kerakyatan). Dalam konsep ini, masyarakat berdaya untuk keluar dari kemiskinan. Pemerintah dalam kapasitasnya untuk memfasilitasi dan menyusun regulasi sebagai “aturan main” yang disepakati.
Mengukur kemiskinan di tingkat desa atau kampung perlu mengembangkan metode berbasis perspektif kerakyatan. Biarkan rakyat yang menghitung dirinya sendiri (people can count) dimana posisi mereka dalam peta kemiskinan di desanya. Mengadopsi teknik forecasting dalam analisis kebijakan, yakni teknik Delphi, maka teknik serupa bisa pula dikembangkan untuk memetakan kemiskinan di desa. Syaratnya, semua pihak memiliki posisi setara untuk mengambil keputusan dan tidak ada intervensi dari mereka yang memiliki kekuasaan secara politik dan ekonomi di desa tersebut. Selain itu, harus ada transparansi dan kejelasan parameter dalam mengukur kemiskinan dan setiap pihak memiliki tanggung jawab bersama atas hasil yang diperoleh. Komunitas di desa atau kampung juga memiliki kewajiban mendesain bagaimana program dan kegiatan yang sesuai untuk membantu mereka yang miskin. Sekali lagi, teknik Delphi membantu masyarakat mengembangkan desain yang lebih mengena pada kelompok RTSM.
Menurunkan model collaborative governance ini hingga struktur terendah administrasi pemerintahan, seperti desa dan kampung memang bukan hal mudah. Ini tak lain adalah strategi mengumpulkan energi pemerintahan hingga pada tingkat terbawah. Namun, hegemoni pemerintah selama ini dalam formulasi dan manajemen kebijakan, khususnya terkait pengentasan kemiskinan, memang merupakan hal yang sulit diterobos. Tidak perlu ada kekhawatiran wibawa pemerintah akan turun apabila desentralisasi diberikan hingga ke tingkat desa. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas anggaran tetap memiliki peran dalam memfasilitasi dan mengontrol berlakunya program dan kegiatan tersebut di desa. Pemerintah perlu membuka diri terutama bagi partisipasi masyarakat yang hendak turut mengembangkan potensi diri dan tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah. Dengan demikian, pemerintah justru akan lebih terbantu saat RTSM dengan potensinya sendiri mampu keluar dari kemiskinan dengan fasilitasi yang diperankan pemerintah.
Konsep yang ditawarkan ini baik secara teoritik maupun metodologi bukan sesuatu yang baru. Namun, melihat penurunan angka kemiskinan yang lambat dan naiknya angka ketimpangan, maka harus ada tawaran perubahan kebijakan melalui model-model kebijakan yang tidak biasa. Keunggulan model collaborative governance atau perspektif kerakyatan ini adalah kemampuannya memahami kemiskinan pada “akar rumput” sehingga desain kebijakan dan manajemen program pengentasan kemiskinan akan lebih mengena bagi kelompok sasaran, khususnya RTSM. Tulisan ini juga bertujuan untuk “menggusur” program-program pengentasan kemiskinan yang selalu bersifat top-down. Kekurangan dari pendekatan top-down ditutup oleh pendekatan yang lebih merakyat atau bottom-up. Maka, model tata kelola yang ditawarkan adalah collaborative governance atau perspektif kerakyatan dalam kebijakan dan program pengentasan kemiskinan di Indonesia.[] Agus Heruanto Hadna, Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM dan Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM.
*Sumber: Harian Jogja (11/4) | Photo Agus Hadna/dok.cpps